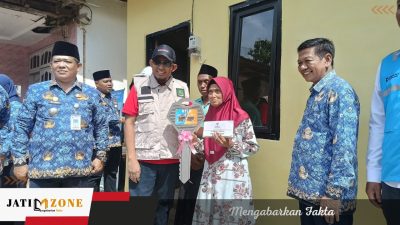Oleh : Tadjul Arifien R
JATIM ZONE – Sejak jaman dahulu, di Sumenep atau Madura selalu ada rumah keluarga besar yang dikenal dengan istilah taneyan lanjang. Terutama di pedesaan yang merupakan kebiasaan masyarakat lokal yang kemudian menjadi tradisi.
Dalam perspektif pemukiman taneyan lanjang, pasti selalu ada roma patobin/tonggu (rumah induk atau utama) yang dibangun pertama kali dan posisinya berada di ujung barat sisi utara dan menghadap ke selatan yang di depannya ada bangunan dapur yang menyatu dengan kandang sapi dengan bentuk memanjang dan menghadap ke utara.
Demikian dalam perjalanan semisal kelak orang tuanya meninggal dunia, maka rumah induk tersebut akan ditempati oleh anak perempuan pertama dengan suaminya.
Roma poto (rumah untuk anak selanjutnya) dibangun di sebelah timur rumah induk menghadap ke selatan, dan selanjutnya dibangun di timurnya sampai batas pamengkang (pekarangan) yang ada.
Kemudian pindah ke sebelah selatan menghadap ke utara, dan pada pagar sebelah timur ada pintu pagar dan akan berbentuk taneyan lanjang.
Pada umumnya, bangunan baru tersebut disediakan untuk anak perempuan bersama suaminya kelak, karena anak laki-laki pada umumnya ikut istrinya kumpul dengan mertuanya.
Sementara dhapor (dapur) dan kandhang (kandang) sapi biasanya disatukan dalam bentuk bangunan yang sama, hanya dipisah oleh tabing (gedek). Tipe dhapor dan kandhang ini lebih kecil dari ukuran rumah tinggal dan lebih mandhap (rendah) dan menghadap ke utara. Sehingga orang yang mau masuk harus agak merendahkan tubuhnya atau kepalanya.
Dhapor dan kandhang sapi dibuat dari bahan kayu dan dindingnya dibuat bidhik (bambu yang dianyam). Dapur fungsinya untuk memasak sedangkan kandang tersebut berisi sapi sebagai hewan piaraan yang umum di Sumenep (Madura).
Kemudian juga ada Kobung atau langgar. Bagi masyarakat Madura, langgar ini memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya didefinisikan sebagai ruang ibadah, namun langgar menjadi identitas taneyan lanjang, hal ini tercermin dari pola aktivitas penghuni, dan bagaimana cara penghuni memperlakukan langgar pada bagian kobung (langgar).
Langgar sebagai tempat musyawarah keluarga, makan bersama keluarga, menerima tamu, sholat berjamaah, tempat ngaji, dan tempat tidur bagi anak atau keluarga laki-laki yang masih belum menikah.
Detailnya, langgar ini dikhususkan untuk menerina tamu laki-laki sedangkan tamu perempuan diterima di serambi rumah.
Pada bagian langgar, mulanya menggunakan tabing (anyaman bambu) sebagai dindingnya sehingga tidak terdapat ornamen.
Seiring perkembangan waktu, ada pergeseresan hingga dindingnya menggunakan batu bata, kobung sangat jarang terdapat ornament yang ada hanyalah berupa relief sederhana berupa motif okel yang sangat sederhana (hanya berupa tangkai utama/tidak ada daun).
Dan pada umumnya, saat ini langgar atau kobung namanya berubah atau masyarakat biasa menyebutnya dengan musholla.
Budaya lokal berbasis taneyan lanjang dilestarikan oleh masyarakat Sumenep (Madura) semata-mata karena terikat dengan “titah” leluhur dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan demi menjaga keseimbangan ekosistem natural dan supranatural.
Filosofi tertinggi etnik Madura adalah agama Islam, wajar jika dirumah adat taneyan lanjang selalu ada langgâr atau kobung atau istilah sekarang Mushalla.
Sementara taneyan lanjang, memiliki arti yang filosofi yang cukup dalam. Yakni membentuk karakter orang Sumenep (Madura) yang santun, arif, dan bijaksana dalam menghargai orang lain.
Keteraturan posisi, bentuk dan proporsi rumah yang dibangun di kampong meji (kampung menyendiri) atau keliling taneyan lanjang menunjukkan baik penguasaan masyarakat atas pengetahuan menata ruang lingkup huniannya.
Di samping taneyan, untuk mengacu sebidang tanah mereka mengenal adanya pamengkang, pakarangan, kebbhun, talon dan teggal yang system penataan ruang dan peruntukannya berbeda satu dengan lainnya.
Kekompakan masyarakat pedesaan dalam melakukan aktifitas juga menunjukkan rasa solidaritas dan kekompakan yang sangat tinggi.
Dalam membangun rumah, mereka lebih dahulu mengenal istilah gutong rojung song-osong lombung (gotong royong mengusung tempat padi). Seperti yang dilakukan kala akan menanam sabbrang (ketela pohon), yang terjadi di desa Jelbudan Kecamatan Dasuk.
Yang punya tegal cukup menyediakan bu’u’ (istilah makanan dari jagung yang dihaluskan dicampur dengan ketela pohon dan diberi parutan kelapa) untuk sarapan, lalu keluar dengan memukul mata cangkul dan disambut dengan tetangganya memukul juga, yang kemudian mereka berkumpul semua, mengerjakan bersama dan dengan waktu 3 jam selesai.
Kemudian semua makan sarapan bersama yang di tempatkan pada beberapa gaddhang (tampa/nyiru), ngakan saleng jumbu’ (makan saling jumput). Juga hal tersebut dilakukan oleh para penghuni taneyan lanjang, dengan ngakan saleng jhumbu’ (makan bersama dalam satu wadah). Yang menunjukkan bahwa system kekerabatan yang sangat tinggi.